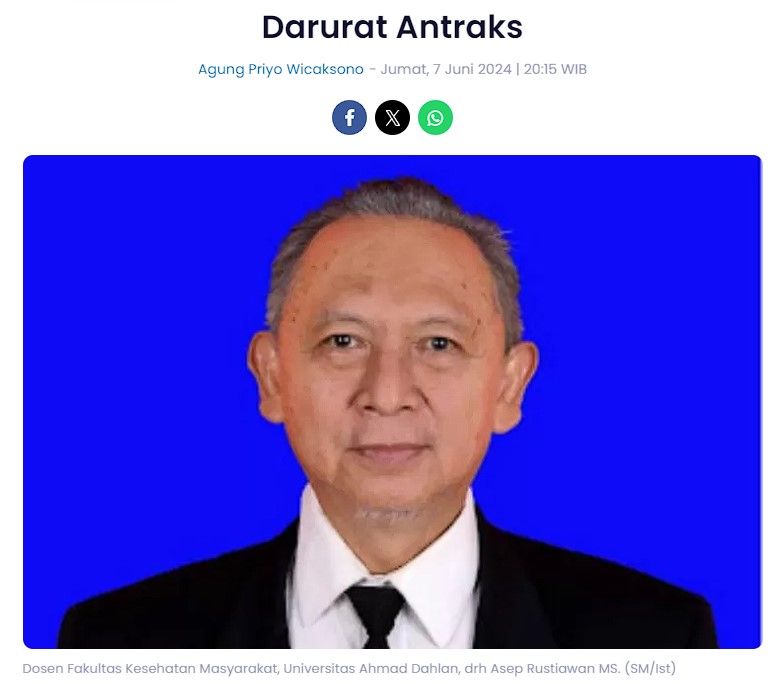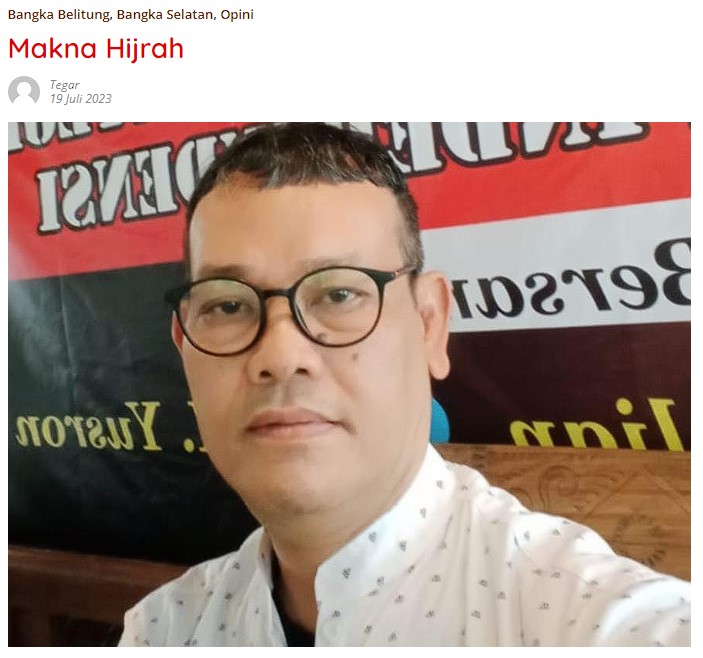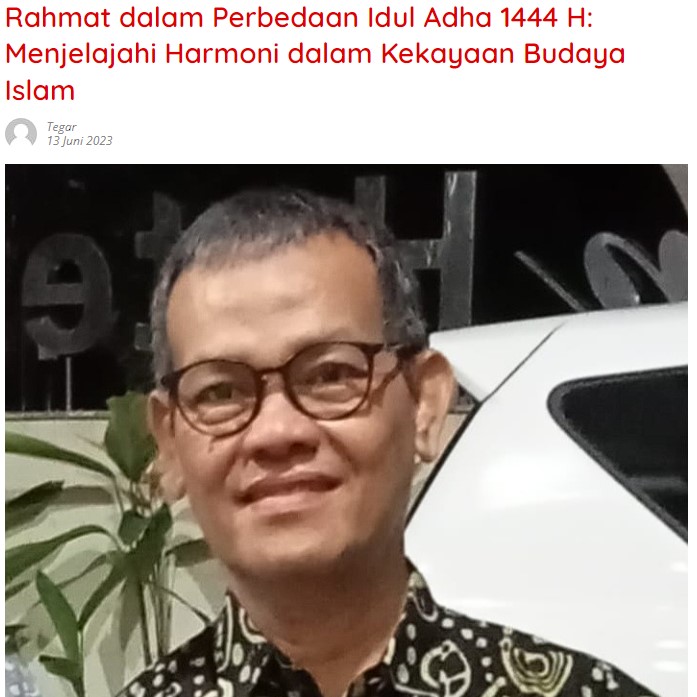Kegamangan Partai dalam Menentukan Kandidat di Pilkada Serentak

Babelpedia (1 Agustus 2023)
Sobirin Malian
Pemilu dan Pilkada serentak 2024 kurang sekitar sembilan bulan, tetapi nampak jelas di berbagai daerah belum nampak jelas siapa kandidat partai yang di usung. Masyarakat pun berteka-teki siapa kiranya kandidat yang akan diusung oleh masing-masing partai. Sejatinya, Pilkada menjadi momentum terbaik partai politik untuk mengusung figur andalannya untuk memenangi kompetisi politik di tiap daerah. Sejauh yang dapat ditangkap partai politik masih bermanuver agar figur yang diusung tidak meleset.
Dari pengalaman partai selama ini, memang menentukan (kandidasi) diwarnai dengan proses yang tidak mudah sehingga sejumlah partai baru benar-benar dapat memastikannya ketika batas waktu makin mendekati masa batas pendaftaran. Pencalonan (kandidat) sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana pengelolaan organisasi partai yang didalamnya mencerminkan implementasi demokrasi internal.
Dari berbagai pemberitaan di media off line dan media on line, bagaimana potret bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai pada Pilkada 2024 ? Dalam kandidasi, tujuan yang diinginkan partai adalah memunculkan kandidat yang kompeten, berintegritas, diterima publik, dan mampu menerjemahkan platform (ideologi) partai dalam berbagai kebijakan. Melalui kandidatnya diharapkan kinerja gemilang partai ikut terangkat, mengapa ? karena selama ini kiprah partai politik dipandang secara pesimistis tidak akan membawa harapan perbaikan. Bahkan, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, citra tiang demokrasi ini dinilai kian memburuk.
Buruknya citra partai politik (parpol) saat ini tak lepas dari beragam sikap dan langkah yang ditampilkannya di hadapan publik selama ini. Kinerja parpol dalam segala bidang kegiatan lumpuh. Sementara itu, perpecahan di dalam partai serta dugaan keterlibatan anggota- anggotanya di dalam perkara korupsi menjadikan publik cenderung menilai negatif partai politik. Oleh karena itu, tak berlebihan jika kemudian harapan politik ikut disematkan, melalui keberhasilan memenangi Pilkada 2024, terutama di daerah yang dianggap strategis dan sebagai lumbung suara seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Partai Belum Siap Pencalonan (penentuan) kandidat terutama kalau yang berasal dari internal partai umumnya partai itu sendiri belum siap. Dalam hal ini, maka semua partai membuka kesempatan kepada pihak terutama eksternal untuk didominasikan. Melalui pencalonan terbuka ini memungkinkan partai mencalonkan figure di luar kader partai. Persyaratan, seperti berapa lama masa kenaggotaan partai, tak dipersoalkan. Figur-figur dengan latar belakang militer, kepolisian, ormas, birokrat, selebritas, tokoh agama dan pengusaha__kini bisa menjadi kandidat partai. Mengapa partai membuka peluang lebar dari eksternal ?
Disadari, proses pengkaderan di partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan gelaran pilkada yang serentak, menuntut partai menyediakan stok kader yang tidak sedikit untuk bisa dinominasikan. Ketidakmampuan partai mempersiapkan kader pada pilkada yang waktunya sudah ditetapkan jauh-kauh hari oleh KPU, menggambarkan partai lebih memilih “keputusan” di waktu-waktu akhir.
Kemungkinan lain, dalam upaya memenangi pilkada seringkali dihadapkan pada seberapa jauh kandidat memiliki peluang menang. Tidak jarang aspek ini dimiliki oleh figur dari eksternal karena sederet rekam jejak figur yang moncer ketika menjabat atau piawai di bidang masing-masing, contoh Anies Baswedan yang dicalonkan Nasdem, PKS dan Demokrat dalam konstatasi Presiden 2024 mendatang. Memang ketika stok kader tidak tersedia dalam internal partai, upaya meminang figur eksternal adalah pilihan yang tak dapat dihindarkan.Tentu pilihan itu bukan tanpa resiko terutama nanti di saat setelah menang harus mampu menerjemahkan platform (ideologi) partai tadi.
Bagaimanapun memilih fidur eksternal pun sejatinya tidak mudah. Hal ini akibat adanya ketentuan electoral threshold dan dinamika koalisi partai dalam pengusungan kandidat. Kalau pun hasil dari kandidasi internal partai memutuskan mengusung figur hasil seleksi, itu pun tidak menjamin akan mulus disepakati oleh mitra koalisi. Penentuan dan pilihan siapa yang diusung menjadi nomor satu (kepala) atau dua (wakil) juga aspek yang sangat menentukan dan dapat menimbulkan friksi yang dapat menajam. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi, saat ujung keputusan bagaimana sebetulnya kemauan konstituen sebagai penentu suara. Jika hal ini tidak diperhatikan dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kader atau pemilih maka bisa berimplikasi munculnya kekecewaan dan eksodus besar-besaran. Sudah kita lihat, ada partai mengusung yang tidak sejalan dengan kader akhirnya kader memilih “kandidat” yang berbeda dengan yang diusung partai. Ada penggembosan suara partai disini.
Elit Penentu Hiruk pikuk penentuan kandidat, diluar yang telah dikemukakan di atas sering juga memperlihatkan proses yang elitis. Dalam artian, keputusan mengenai figur yang diusung kadang-kadang dalam suasana senyap karena lebih banyak ditentukan oleh elit partai. Pemimpin partai dengan lingkaran elit pengurus khususnya di Indonesia__ memiliki pengaruh besar untuk memutuskan bakal calon (kandidat). Terlebih pada partai dengan pemimpin sentral atau sosok paling berpengaruh yang sangat menentukan. Dengan tipe partai seperti ini hanya elit partai yang memiliki akses kedekatan dengan pemimpin yang bisa ikut memberi sumbangan pengaruh dalam beragam keputusan partai, termasuk bakal calon. Kuatnya pengaruh figur pemimpin ini membuat penetapan bakal calon bisa tampak lebih karena selera atau faktor kedekatan dengan elit partai.
Dalam kandidasi elitis tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa melahirkan praktik politik uang atau transaksional, seperti dugaan adanya biaya politik bakal calon yang ingin diusung. Yang menjadi persoalan keputusan elit partai bisa juga menimbulkan persoalan karena tidak “terbuka” bagi anggota partai lain atau publik; padahal salah satu wujud kedaulatan partai adalah terlibatnya anggota dalam sejumlah kebijakan partai, termasuk penentuan bakal calon. Pelibatan dan partisipasi dari anggota partai diperlukan mengingat dalam kesempatan itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa penentuan bakal calon dilakukan melalui makanisme yang transparan dan akuntabel. Termasuk nanti partai harus berkoalisi.
Akhirnya, sudah saatnya partai senafas dengan substansi demokrasi yaitu bersifat transparan dan akuntabel bukan elitis. Partai memiliki peluang menempatkan seluruh komponennya mengikuti proses pencarian bakal calon kepala daerah yang diharapkan nanti bisa kompetitif. Partai juga bisa mempersiapkan diri sedini mungkin dalam menghadapi Pilkada. Dengan persiapan yang lebih dini, matang tentu partai tidak lagi gamang dalam menyiapkan bakal calon yang akan diusung. Wallahu ‘alam bissawab.
Sumber : https://babelpedia.id/kegamangan-partai-dalam-menentukan-kandidat-di-pilkada-serentak/