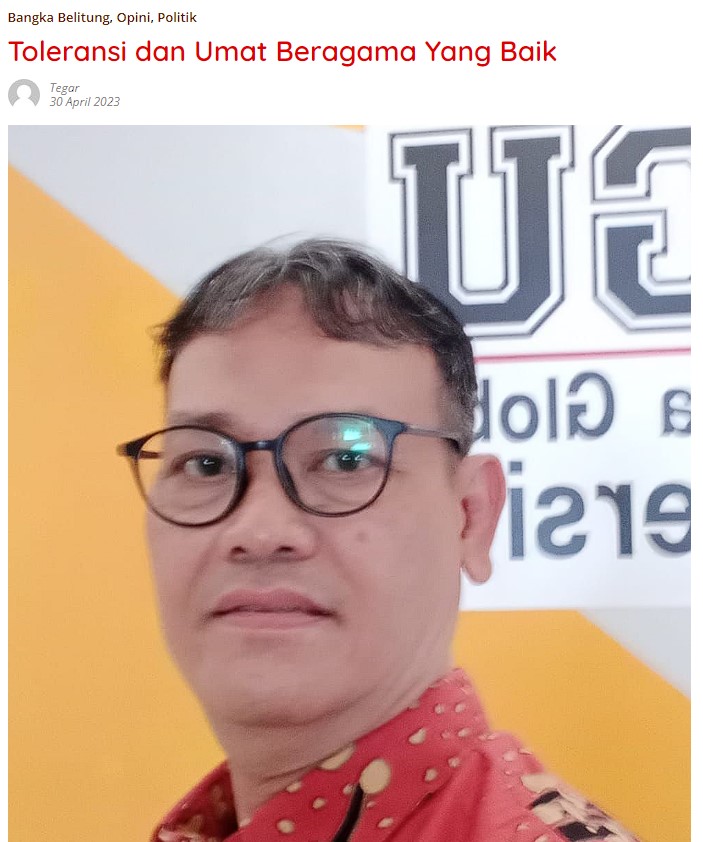Times Indonesia (13 Februari 2023)
Imam Azhari
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Proses pembelajaran merupakan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan kapasitas mereka untuk menyelesaikan tugas yang secara tidak langsung menunjukkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Dalam mencapai keterampilan pemecahan masalah, siswa perlu mendapatkan bimbingan tentang cara menggali ide-ide dasar dan langkah-langkahnya. Sekaligus mengukur bahwa hasilnya mencerminkan tingkat kreativitas mereka.
Dalam pengertian ini, keterampilan design thinking menjadi penting untuk dipelajari karena terdiri atas urutan langkah proses yang fleksibel dan berulang. Oleh karena itu, design thinking dapat digunakan sebagai alat yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad 21, yakni kreativitas.
Design thinking telah diterapkan dalam banyak kegiatan industri dan dunia komersial. Saat ini, minat terhadap desain tidak hanya meningkat di bidang desain produk atau layanan, tetapi design thinking juga telah dimanfaatkan ke sektor publik, dan banyak sektor lainnya. Sebagian besar minat dalam design thinking didasarkan pada kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, teknologi, dan politik yang merupakan bagian dari kompleksitas global baru.
Konsep Design Thinking
Design thinking dideskripsikan sebagai cara berpikir atau proses kognitif yang diwujudkan dalam tindakan merancang proses pemikiran (Cross, 2007; Dunne & Martin, 2006). Design thinking juga didefinisikan sebagai proses kognitif yang digunakan oleh para desainer, bukan menunjukkan objek hasil kegiatan perancangan. Lebih lanjut, design thinking merupakan konsep yang menyeluruh mengenai proses pembelajaran dan perancangan yang memungkinkan para siswa belajar secara multidisiplin. Sebagai pendekatan proses pemecahan masalah, design thinking telah terbukti dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial sehari-hari yang kompleks yang sulit untuk dipecahkan (Brown, 2008).
Dengan demikian, design thinking menawarkan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang terdefinisi dan tidak mudah dipahami. Design thinking fokus pada penyelesaian masalah dengan menciptakan ide-ide (produk, layanan, sistem) untuk masalah yang rumit dan menawarkan pendekatan baru untuk sekelompok orang tertentu (Lindberg et al., 2010).Design thinking juga merupakan konsep multidisiplin yang menyediakan kerangka berpikir kreatif (Lindberg et al., 2010). Strategi pengajaran berbasis design thinking berfokus pada berbagai disiplin dan melibatkan perspektif yang luas (Brown, 2008).
Karya kreatif membutuhkan kreativitas, dan kreativitas adalah keterampilan berpikir inti abad kedua puluh satu bagi siswa. Para peneliti merekomendasikan bahwa kreativitas juga aspek penting yang perlu dikuasai bagi para guru, tetapi mengingat tantangan dan kesulitan yang dihadapi para guru, kreativitas sering dianggap sebagai kegiatan santai di kelas (Root-Bernstein & Root-Bernstein, 2017).
Design thinking menyediakan struktur yang fleksibel dan mudah diakses untuk memandu para guru, dan untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam menangani masalah-masalah praktis. Selain itu, para praktisi design thinking menegaskan bahwa keterampilan design thinking merupakan kunci kreativitas abad ke-21.
Meskipun design thinking sering digunakan dalam dunia bisnis, desain produk dan layanan, metode ini juga berpotensi diterapkan di dunia pendidikan. Potensi pemanfaatan design thinking dalam implementasi kurikulum dan meningkatkan aspek pedagogis telah dipertimbangkan oleh banyak peneliti pendidikan (Laurillard, 2012).
Pendekatan Design Thinking dalam Pendidikan
Design thinking adalah metode pendekatan proses desain yang menawarkan solusi untuk suatu masalah. Pendekatan ini sangat mempengaruhi cara pengambilan keputusan yang akan menghasilkan ide-ide baru dan inovatif di bidang pendidikan. Bagian berikut ini membahas pendekatan design thinking dalam pendidikan dengan memfokuskan secara lebih mendalam tentang design thinking dalam pendidikan melalui pendekatan pedagogis.
Design Thinking dalam Pendidikan
Design thinking sering disebut sebagai paradigma baru untuk menangani masalah di banyak profesi dan bidang, termasuk teknologi informasi, bisnis, penelitian, inovasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, design thinking dapat dianggap sebagai alat yang hebat untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad kedua puluh satu (Glen et al., 2014).
Sebab, design thinking melibatkan kolaborasi untuk memecahkan masalah dengan menemukan dan memproses informasi, dengan mempertimbangkan fakta-fakta lapangan, pengalaman dan umpan balik para pemangku kepentingan yang terlibat, dan dengan menerapkan kreativitas, pemikiran kritis, dan komunikasi (Ray, 2020).
Dalam beberapa literatur, design thinking terkadang disebut sebagai “pembelajaran berbasis desain”, yang dapat dipahami sebagai “model untuk meningkatkan kreativitas, daya tahan, partisipasi, dan inovasi” (Dolak et al., 2013). Manfaat desain thinking dalam pedagogi mengacu pada cara “menjadikan siswa untuk mampu belajar dengan baik dalam tim dan diarahkan secara terstruktur dalam tahapan perancangan penyelesaian masalah sehari-hari” (Kijima et al., 2021).
K.H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan seyogyanya melahirkan manusia-manusia tangguh yang siap menghadapi problem masa depan (Citraningsih, 2021). Untuk itu pendidikan merupakan sistem yang masif dan dirancang secara kolektif. Sekolah dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan fungsionalitas.
Namun, keterbatasan sistem sekolah tradisional telah mengilhami upaya serius untuk melakukan terobosan bagaimana pendidikan harus melahirkan generasi yang mampu mengatasi tantangan saat ini, dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Selain itu, penting juga untuk memperkaya lingkup pendidikan guru, karena guru semakin ditantang untuk menjadi kreatif dan menggunakan praktik baru untuk konteks pendidikan abad ke-21 (Pendleton-Jullian & Brown, 2015).
Proses Pendidikan Menggunakan Design Thinking
Keterampilan design thinking juga dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam kerja kelompok dan proyek, karena salah satu prasyarat design thinking adalah kerja tim dan komunikasi yang terbuka antar anggota tim (Kijima et al., 2021). Ray (2020) menyarankan bahwa bekerja dalam kelompok kecil, dan terdiri atas 6 langkah yaitu mengidentifikasi peluang, desain, membuat prototipe, mendapatkan umpan balik, scale and spread, serta presentasi.
Langkah 1: Identifikasi Peluang. Langkah ini dapat dilakukan sebagai kegiatan di kelas, atau sebagai kerja kelompok. Selama tahap ini, siswa harus mengidentifikasi kebutuhan masalah yang akan dipecahkan, serta siapa saja yang akan mendapat manfaat dari solusi tersebut.
Kemudian, siswa memilih beberapa orang yang terpengaruh oleh masalah tersebut, untuk berbagi pengalamannya. Siswa harus mewawancarai mereka. Ini bisa dilakukan secara pribadi, melibatkan kegiatan di luar kelas; sebagai alternatif, orang-orang ini dapat diundang untuk berpartisipasi dalam pelajaran atau wawancara dapat diselenggarakan melalui platform daring.
Langkah 2: Proses Desain. Selama fase ini, siswa mengulas hasil wawancara yang diperoleh pada langkah 1, dan mencari berbagai alternatif solusi. Salah satu cara yang dapat ditempuh pada langkah ini memanfaatkan pulpen dan sticky-note warna-warni, dan membiarkan mereka melakukan brainstorming solusi.
Dalam tahap ini, siswa didorong untuk mengatakan “Ya” ketika mereka setuju dengan ide masing-masing, dan “Ya, tapi …” ketika mereka tidak setuju. Hal ini dilakukan agar tidak menyurutkan siswa lain untuk mengungkapkan pendapatnya, dan untuk mencari ide-ide alternatif.
Langkah 3: Prototipe. Selanjutnya, tim melakukan diskusi untuk membahas ide-ide yang berhasil dikumpulkan dan memilih satu prototipe. Prototipe yang dipilih ini harus dapat menyelesaikan satu aspek dari masalah. Pada titik ini, siswa akan fokus pada satu solusi yang ditawarkan untuk memecahkan aspek tertentu dari masalah yang diberikan. Kemudian siswa memilih aspek masalah berikutnya dan mendekatinya dengan cara yang sama secara berulang. Untuk memvisualisasikan proses berpikir, disarankan untuk menggambar dalam bentuk diagram atau grafik yang menunjukkan proses ini. Diagram ini juga dapat dibuat dengan menempelkan catatan tempel (sticky note) pada kertas.
Langkah 4: Umpan balik. Dalam tahap ini, tim mempresentasikan solusi mereka kepada pihak eksternal atau tim-tim yang lain untuk mendapatkan umpan balik. Disarankan untuk memiliki setidaknya dua pakar atau guru yang memiliki minat terhadap masalah yang sedang dipecahkan.
Langkah 5: Scale and spread. Selama tahap ini siswa bekerja dalam tim untuk menemukan solusi terbaik dari umpan balik yang diterima dari tahap sebelumnya. Dalam proses ini, bantuan guru dalam membimbing ide-ide siswa sangat diperlukan untuk mempertajam hasil yang diperoleh. Jika tim tersebut menerima banyak pandangan dari pakar atau guru, kelompok tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, dengan masing-masing kelompok mengerjakan satu masalah. Sub-kelompok kemudian dapat berkumpul dan menyepakati hasil akhirnya untuk presentasi.
Langkah 6: Presentasi. Tim mempresentasikan solusi mereka untuk masalah yang diselesaikannya. Sesi presentasi ini dapat menghadirkan para pemangku kepentingan yang diwawancarai siswa selama tahap.
Aktivitas pembelajaran terstruktur semacam ini merupakan kesempatan bagi siswa untuk memecahkan masalah dunia nyata dan menawarkan solusi bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tidak ada solusi yang buruk atau salah, karena menurut teori pendekatan design thinking, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda (Rittel & Webber, 1972). Tantangan bagi guru bahwa kegiatan ini memakan waktu dan tidak dapat dilakukan dalam satu pelajaran. Seperti halnya aktivitas berbasis proyek, ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga guru dapat memandu proses dengan menetapkan batas waktu yang pasti untuk setiap bagian dari aktivitas yang harus dilakukan. Guru dapat menyesuaikan materi yang ada dengan kebutuhan pedagogis para siswa untuk memotivasi belajar siswa.
Tantangan Penerapan Design Thinking
Dalam pembahasan tersebut terlihat bahwa design thinking dapat diterapkan sebagai bagian penting proses pengajaran dan pembelajaran. Design thinking adalah proses pembelajaran yang efektif yang meningkatkan kreativitas, membangun keterampilan, membantu siswa berpikir out of the box, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membantu menonjolkan bakat siswa (Tsalapatas et al., 2019). Namun, ada juga beberapa tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam menerapkan pendekatan design thinking ini.
Tantangan untuk Guru
Bagi guru, menyampaikan materi pengajaran yang sistematis dan efektif, dibutuhkan persiapan bahan pembelajaran untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan efektif. Kurangnya pengalaman guru dalam penggunaan design thinking untuk pembelajaran di sekolah merupakan tantangan lain yang dihadapi guru dalam memberikan informasi yang cukup dan relevan dalam menggunakan metode design thinking ini. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman atau kebingungan di kalangan siswa, ketika guru tidak dapat memberikan arahan kepada siswa pada saat pembelajaran berlangsung.
Selain itu, diperlukan waktu yang cukup bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan design thinking dengan pembelajaran di kelas untuk memastikan siswa memahami materi pembelajaran, sementara itu waktu yang dialokasikan untuk guru sangat singkat, dan jadwal guru juga terlalu padat, sehingga menyebabkan kurangnya waktu untuk pembelajaran siswa.
Selain itu, juga dibutuhkan pelatihan tentang design thinking dalam pendidikan untuk memberikan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendidik untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam pembelajaran yang akan diajarkan di kelas agar meningkatkan minat belajar siswa.
Tantangan untuk Siswa
Ketika siswa belajar menerapkan design thinking untuk pertama kalinya dalam kegiatan belajar, mereka akan mengalami kebingungan dan bahkan frustrasi, karena mereka akan mencoba memahami dengan pemikiran masing-masing ketika mereka diberi proyek untuk ditangani. Para peneliti menyarankan agar siswa mempelajari sumber-sumber bacaan yang memadai terkait masalah yang akan diselesaikan terlebih dulu agar memahami perspektif yang diperlukan untuk memulai pembelajaran menggunakan design thinking.
Selain itu, siswa dapat mengalami kesulitan karena kurangnya kreativitas ketika siswa harus menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan ini. Mereka tidak melihat masalah sebagai peluang untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, kreativitas adalah landasan terpenting untuk menerapkan pendekatan design thinking dalam pendidikan.
Tantangan lain yang dihadapi siswa ketika belajar melalui design thinking adalah kurangnya ide yang bagus untuk merancang proyek seperti yang diminta oleh guru mereka. Kurangnya ide ini akan menyebabkan siswa untuk menerima begitu saja, dan mereka tidak akan bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh gurunya. Dengan munculnya ide-ide bagus, siswa akan lebih bersemangat dan lebih terlibat dalam kegiatan kelas.
Selain itu, siswa mungkin menghadapi tantangan kerja tim dalam melakukan proyek di kelas karena konflik atau kesulitan dalam tim mereka, karena perbedaan pendapat dan kurangnya kerja sama. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi juga akan menyebabkan kurang kompaknya kerja sama tim antar siswa. Kerja tim sangat penting dalam design thinking karena membutuhkan banyak pendapat untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
Dampak Design Thinking
Design thinking menantang siswa dan guru untuk menerapkan berbagai bentuk pengetahuan, termasuk keterampilan sosial, teknologi, dan lainnya. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang menuntut siswa untuk memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang mata pelajaran tertentu.
Tentu saja ada kendala dalam penggunaan design thinking dalam pendidikan, seperti tantangan bagi guru dan siswa. Di antara tantangan yang dihadapi guru adalah: kekurangan sumber daya, kurangnya pengalaman, kendala waktu, dan kurangnya pelatihan. Tantangan design thinking yang dihadapi siswa antara lain kebingungan dan frustrasi, kurangnya kreativitas, kurangnya ide bagus dan kesulitan dalam kerja sama tim.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendidik harus selalu terbuka untuk menerima hal-hal baru dalam pembelajaran yang terkini. Sehingga, mereka memiliki motivasi dan tidak tertekan untuk mengajarkan teknik baru seperti pembelajaran menggunakan design thinking. Selain itu, design thinking juga berdampak besar pada perkembangan guru didalam lembaga pendidikan. Budaya baru ini akan mendorong kesan positif dari proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah, serta pengembangan profesional guru dan pengembangan keterampilan siswa, sebagai bagian penting dari pengajaran abad 21. (*)
Penulis adalah Imam Azhari, Dosen Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Sumber https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/445995/penerapan-design-thinking-dalam-pendidikan-dan-tantangannya