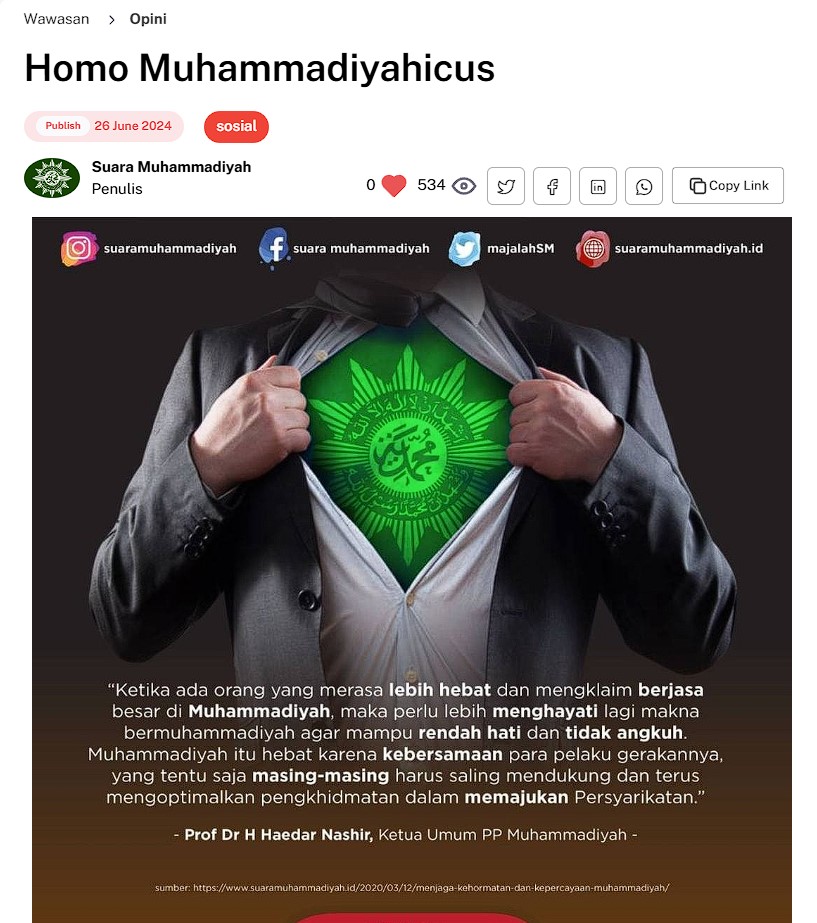Darurat Kesehatan Mental pada Mahasiswa Kesehatan

Harian Jogja (7 Juni 2024)
Lolita
Mahasiswa merupakan individu yang sedang menempuh proses pendidikan akademik, dalam bidang studi tertentu dalam upaya peningkatan pengetahuan, kompetensi, sikap dan keterampilan. Kesehatan merupakan salah satu jurusan yang banyak diminati oleh mahasiswa. Dalam perjalanan menempuh studinya, mahasiswa melewati beberapa permasalahan yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan mental.
Gangguan kesehatan mental pada mahasiswa kesehatan ditandai perasaan tidak nyaman atau ketegangan selama masa studi. Hal ini sering diabaikan, padahal kecemasan memberikan dampak negatif yang memengaruhi kemampuan belajar, mengganggu performance akademik hingga putus kuliah. WHO melaporkan sekitar 300 orang di dunia telah mengalami depresi, di mana 5,2% nya berasal dari Indonesia.
Salah satu faktor utama pemicu gangguan kesehatan mental pada mahasiswa kesehatan yaitu tekanan akademik yang tinggi. Jadwal kuliah dan praktikum yang padat, tugas yang menumpuk, serta berbagai tahap ujian teori praktik tak lepas dari kehidupan akademik mahasiswa kesehatan.
Standar kompetensi yang tinggi baik dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan praktis mengakibatkan tuntutan yang tinggi untuk mempertahankan prestasi. Mahasiswa kesehatan juga dituntut agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan baik oleh perguruan tinggi dan asosiasi. Pada beberapa kasus juga masih ditemukan adanya diskriminasi yang dialami mahasiswa kesehatan akibat persaingan dan ketidakseimbangan sosial.
Kondisi gangguan mental akan terjadi ketika mahasiswa merasa tidak mampu memenuhi semua ekspektasi yang ada. Gangguan kesehatan mental pada mahasiswa kesehatan dapat berdampak negatif pada kinerja akademik dan kehidupan pribadi. Sebagai contoh stres berlebihan pada mahasiswa kesehatan juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar, berkonsentrasi, dan memproses informasi dengan baik. Stres yang berkelanjutan juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik mereka, seperti peningkatan risiko gangguan tidur, gangguan pencernaan, atau gangguan kesehatan lainnya. Peningkatan stres yang dialami oleh mahasiswa kesehatan juga dapat menyebabkan peningkatan iritabilitas. Mahasiswa menjadi mudah tersinggung, mudah marah, atau sulit untuk mengendalikan emosi.
Iritabilitas dapat memengaruhi hubungan interpersonal mereka dengan teman, keluarga, atau teman-teman mahasiswa lainnya. Dampak dari iritabilitas dapat menyebabkan mahasiswa menjadi kurang sabar dalam menghadapi tugas-tugas atau tantangan akademik, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik.
Mengelola Gangguan
Dalam mengelola gangguan kesehatan mental yang dialami oleh mahasiswa kesehatan, penting bagi mereka untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti manajemen waktu yang baik, dukungan sosial yang kuat, perawatan diri yang baik, dan kemampuan untuk mencari bantuan jika diperlukan.
Disamping itu, melakukan banyak aktivitas pribadi menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi gangguan kesehatan mental pada mahasiswa. Salah satu caranya dengan mengembangkan hobi, latihan meditasi, memanfaatkan teknik relaksasi, dan manajemen stres. Melukis, menggambar, menulis, atau membuat musik dapat menjadi cara yang efektif untuk mengekspresikan dan mengelola emosi.
Aktivitas seni ekspresif ini dapat membantu mahasiswa kesehatan mengalihkan perhatian dari pikiran yang negatif dan merasa lebih tenang dan terhubung dengan diri mereka sendiri. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam-dalam, dan relaksasi progresif otot dapat membantu meredakan kecemasan dan stres. Mahasiswa kesehatan dapat mencoba berbagai teknik relaksasi dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Di samping itu juga, institusi pendidikan juga wajib menyediakan sumber daya dan dukungan yang tepat, seperti layanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan manajemen stres, dan program mentoring. Upaya deteksi dini dan penanganan gangguan kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman dan sehat untuk mencapai potensi penuh sebagai profesional kesehatan yang berdedikasi dan berempati. Dengan dukungan yang tepat, keberanian dan kepercayaan diri yang kuat, mahasiswa kesehatan siap untuk membawa perubahan positif dalam dunia kesehatan.