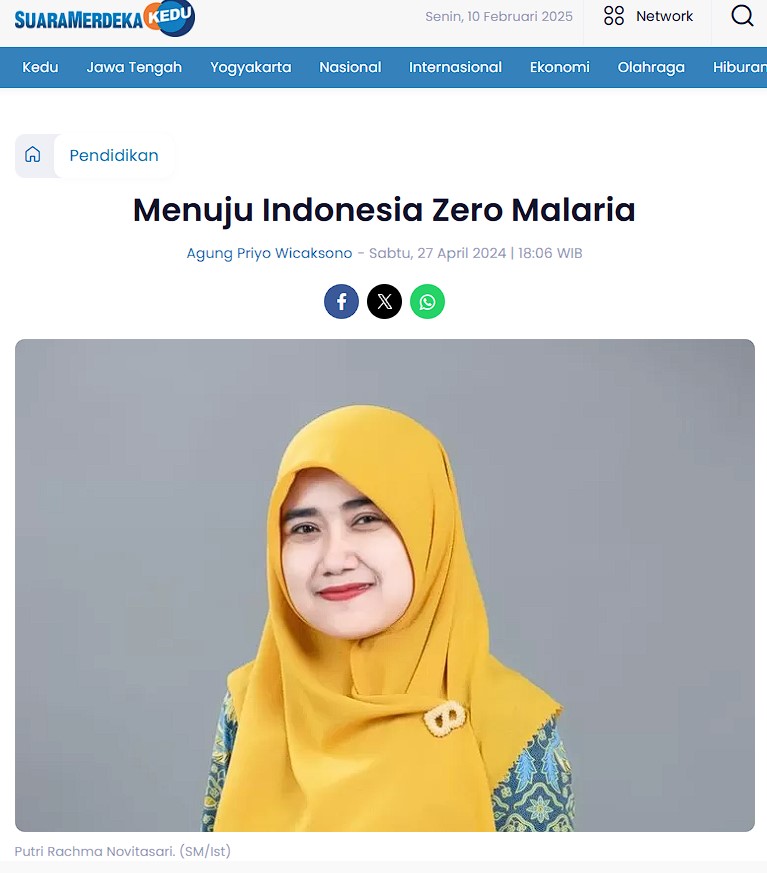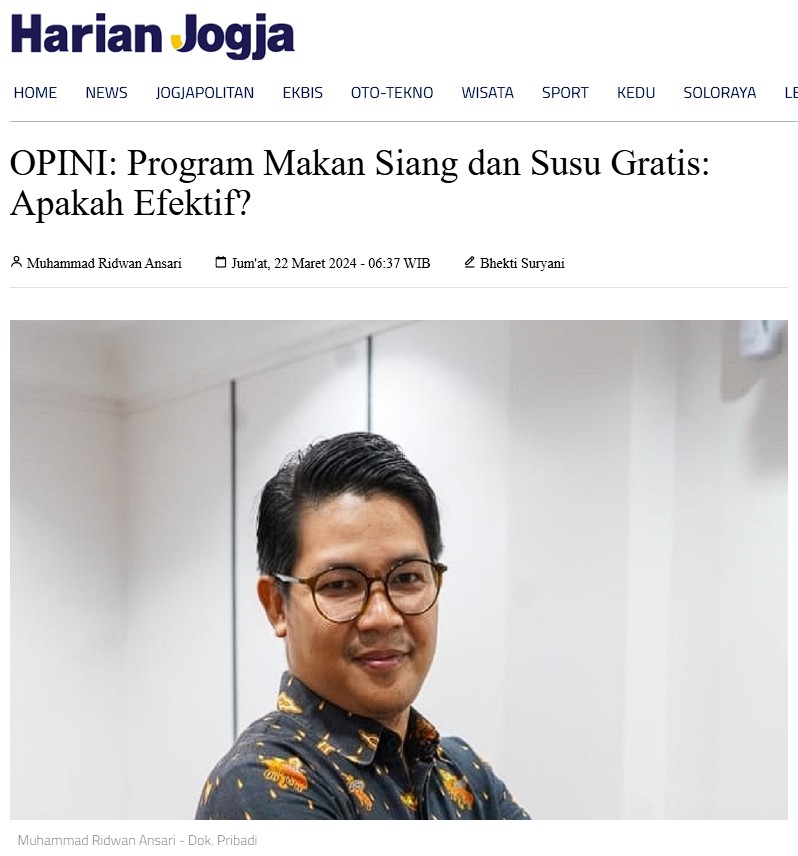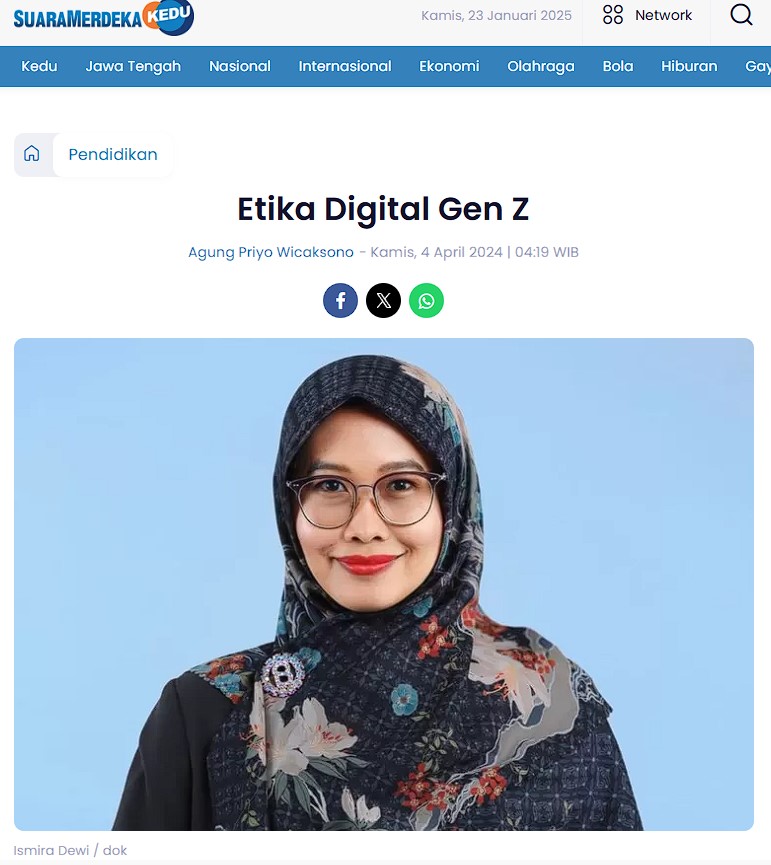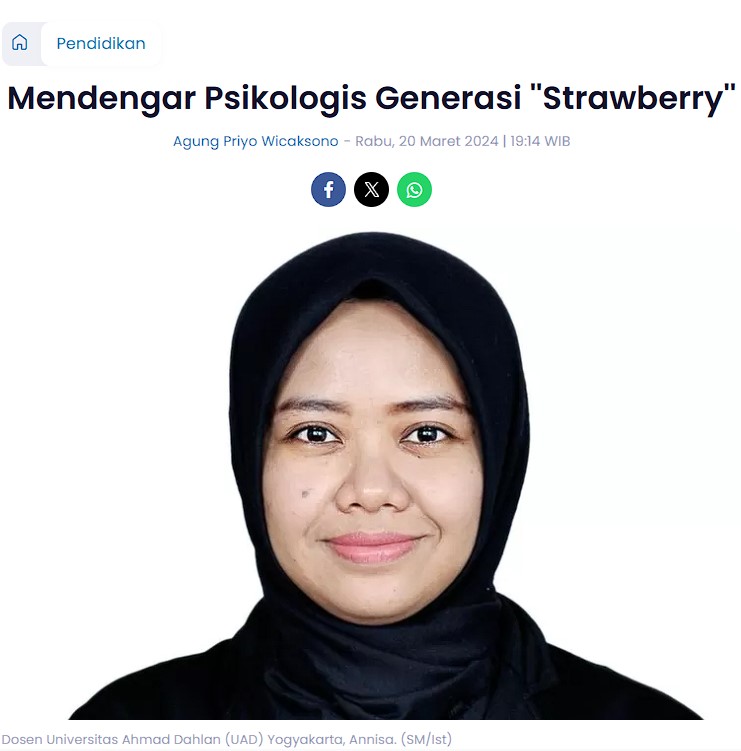Warga Kelas Dua dan Demokrasi Berkemajuan

Suara Aisyiyah (7 Februari 2024)
Annisa Fithria
Budaya patriarki di Indonesia memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, menciptakan sistem sosial yang didominasi oleh pria, dan menempatkan perempuan dalam peran yang lebih rendah sebagai warga kelas dua. Di era modernitas seperti sekarang, pada tingkat makro, peran tradisional gender masih menetapkan norma-norma patriarki, dengan laki-laki dianggap sebagai tulang punggung keluarga dan pemimpin, sementara perempuan diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak.
Kondisi seperti ini disebabkan oleh pola didik yang tidak setara sejak dalam rumah dimana ethics of care menjadi pendidikan dominan yang didapatkan oleh perempuan seolah perempuan hanya dituntut fokus pada urusan domestik rumah tangga sedangkan laki-laki diasuh dengan pola didik ethics of justice dengan mengumpamakan hanya lelakilah yang boleh membahas dan duduk pada diskursus politik, keadilan, dan kebijakan publik. Padahal, pendidikan ethics of justice sama pentingnya dengan pendidikan ethics of care dimana baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan keduanya dan setara kedudukannya untuk seluruh jenis ilmu apapun.
Dampak dari budaya patriarki tidak hanya terbatas pada norma-norma sosial, tetapi juga melibatkan masalah serius, seperti kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat muncul sebagai hasil dari struktur sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022 terdapat 459.094 laporan kekerasan terhadap perempuan dan sekitar 3,2 juta kasus kekerasan seksual dalam 8 tahun terakhir. Diskriminasi gender masih menjadi kendala di berbagai sektor, termasuk dalam pendidikan, partisipasi politik dan demokrasi yang menciptakan ketidaksetaraan yang perlu diatasi.
Dalam partisipasi politik dan pengambilan kebijakan, peranan perempuan juga belum begitu memuaskan walaupun Indonesia telah mengadopsi Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) pada tahun 1984 dalam bentuk UU No. 7 Tahun 1984 yang mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan landasan hukum bagi upaya lebih lanjut dalam mencapai kesetaraan gender serta lahirnya UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur peningkatan kuota perempuan dalam parlemen dan pemerintahan lokal sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
Pencapaian target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen masih jauh dari harapan yang diinginkan. Berdasarkan informasi dari World Bank pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ketujuh di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen dan hanya 120 orang atau 20,9% keterwakilan perempuan di parlemen pada periode 2019-2024. Dalam konteks pemilihan umum anggota DPR tahun 2024, hanya satu partai dari total 18 partai politik yang memenuhi kuota minimum 30 persen kandidat perempuan dalam daftar pencelanonan.
Ketidakcapaian target keterwakilan perempuan sebesar 30% dapat disebabkan oleh faktor-faktor kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegagalan keterwakilan perempuan di legislatif dapat disebabkan oleh sistem budaya politik dan rekrutmen partai yang belum mendukung calon perempuan untuk menjadi anggota DPR RI. Selain itu, sistem pemilu proporsional terbuka juga dianggap melemahkan upaya calon perempuan dalam mendapatkan dukungan suara.
Untuk mengahasilkan demokrasi yang berkemajuan, diperlukan komposisi yang setara terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan partisipasinya dalam politik elektoral. Representasi yang adil dan seimbang dalam demokrasi yang sehat menjadi mungkin dengan melibatkan secara aktif perempuan dalam proses politik. Memastikan bahwa suara mereka diakui dan diwakili dalam pengambilan keputusan politik untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Aktivitas politik perempuan dapat memperkuat kesempatan dan hak-hak mereka untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
Meningkatkan peran perempuan dalam demokrasi memerlukan serangkaian upaya dan strategi. Salah satu langkah kunci adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Program pendidikan yang setara dan penyebarluasan arus informasi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak perempuan terutama dalam konteks politik dan kebijakan publik.
Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum juga diperlukan. Ini dapat dilakukan bukan hanya melalui peningkatan jumlah kandidat perempuan dan penggunaan kuota khusus sebagaimana yang tertera dalam undang-undang, tetapi juga memberikan dukungan finansial dan pelatihan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik guna melampaui dan melawan batas-batas patriarkis yang secara tradisional tumbuh di masyarakat kita.
Perubahan budaya politik yang mendukung stereotip gender dan diskriminasi juga merupakan langkah krusial. Kampanye kesetaraan gender, peningkatan kesadaran, dan promosi nilai-nilai kesetaraan terutama di institusi partai politik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi partisipasi perempuan.
Melakukan audit gender terhadap kebijakan dan praktik politik merupakan langkah krusial dalam mengidentifikasi ketidaksetaraan pada institusi-institusi politik untuk mengevaluasi dan melakukan perubahan yang diperlukan. Melalui serangkaian upaya ini, diharapkan peran perempuan dalam demokrasi dapat ditingkatkan, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan politik, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sangat perlu kiranya kita melakukan evaluasi secara terus menerus untuk menghasilkan sistem dan ekosistem demokrasi yang menjamin bangsa Indonesia benar dalam track menuju cita-cita Nasional. Oleh karena itu demokrasi berkemajuan menjadi mutlak. Demokrasi yang memberikan kesempatan bagi seluruh warga bangsa untuk berpatisipasi dalam keputusan politik dan kebijakan publik. Membuka sebesar-besarnya peluang perempuan dan kaum marjinal lainnya untuk tidak lagi menjadi warga kelas dua dan sama kedudukannya dengan warga lain untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber : https://suaraaisyiyah.id/warga-kelas-dua-dan-demokrasi-berkemajuan/