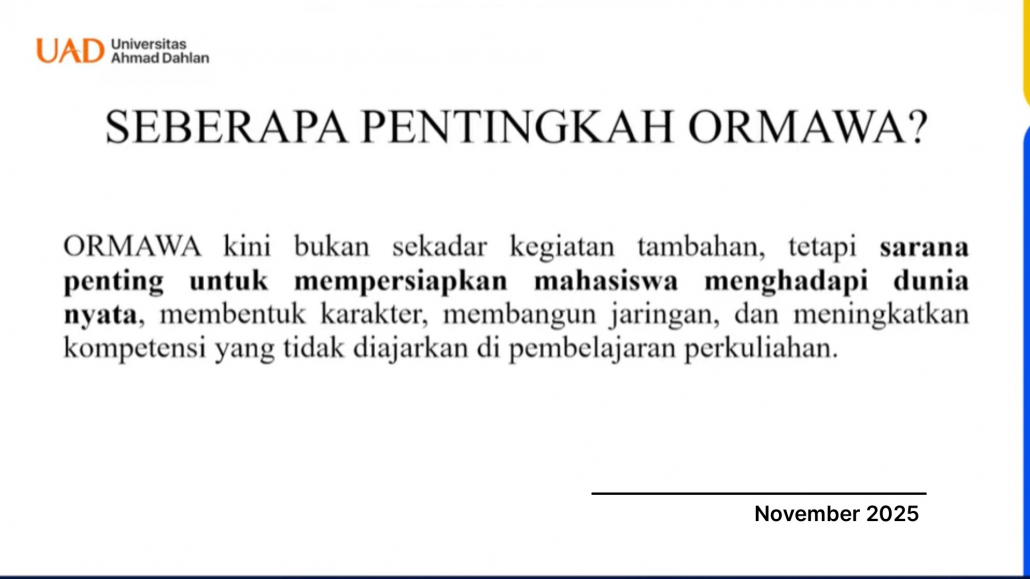Mahasiswa PGSD UAD Raih Dua Penghargaan Juara Esai dan Presenter di Ahmad Dahlan International Seminar #3 2025

Ika Oktavia, Mahasiswa Program Studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Foto. Ika)
Ika Oktavia Saputri, mahasiswa Program Studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan (UAD), berhasil menorehkan prestasi gemilang di tingkat internasional. Ika meraih dua gelar sekaligus, yaitu Juara Harapan Esai dan **Juara Harapan III Presenter dalam ajang lomba esai dan presenter di Ahmad Dahlan International Seminar #3 yang diselenggarakan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BIMAWA) UAD pada 6–31 Oktober 2025.
Awal Ika mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan ini dimulai dengan mencari info di berbagai media sosial UAD tentang adanya lomba esai dan presenter tingkat internasional. Ika sangat antusias dan ketika sudah mendapatkan info, langsung menyusun esai dengan penuh semangat dan berharap mendapatkan juara pada perlombaan ini.
Esai yang disusun Ika berjudul “Facing the Digital Age: Educational Changes that Shape Future Generations”. Ia mengambil tema “Future Education” karena dirasa paling tepat mengingat statusnya sebagai calon guru di masa depan. Ia membuat esai tersebut selama tiga hari dengan penuh semangat dan yakin bahwa itu adalah esai terbaik. Setelah esai selesai, Ika mempresentasikan karyanya tersebut, dan alhamdulillah juga mendapat **Juara Harapan III Presenter di acara Ahmad Dahlan International Seminar.
Tantangan yang dihadapi Ika Oktavia Saputri pada saat mengikuti lomba adalah sering kali sedikit bergelut dengan waktu karena tugas kuliah yang tidak sedikit itu kadang menyita banyak waktu. Ika mau tidak mau harus bisa mengatur waktu itu dengan adil supaya semuanya bisa dikerjakan.
“Persiapan ini memerlukan fokus tinggi untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dan ambisi meraih prestasi,” ujar Ika Oktavia Saputri.
Harapan Ika setelah mengikuti perlombaan ini adalah semoga di hari selanjutnya bisa menjadi lebih baik dalam mengerjakan apa pun itu, dan semoga di lain kesempatan bisa mendapatkan juara yang lebih dari saat ini. (Septia)